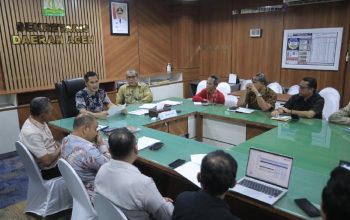BENCANA banjir yang melanda sebagian besar Aceh, telah menelan korban jiwa dan harta benda. Hujan yang turun terus-menerus, seperti kehilangan tombol berhenti. Berhentinya hanya berupa gerimis saja, lalu turun lagi dengan derasnya. Begitu terus selama beberapa hari hingga menyebabkan banjir di mana-mana.
Sesuai prakiraan Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), baru pada 27 November 2025 hujan berhenti sama sekali, setidaknya itu terjadi di Lhokseumawe dan beberapa daerah sekitar. Di tengah kondisi alam yang semakin sulit diprediksi, kehadiran BMKG semakin sentral.
Sayangnya, dalam bencana banjir tersebut BMKG terlambat menyampaikannya ke publik. Seharusnya, peringatan tersebut sudah disampaikan jauh-jauh hari agar pemerintah dan masyarakat bisa awas menghadapi bencana.
Penanganan darurat bencana, seperti yang kini lihat di lapangan, sangat lamban, tidak sigap, tidak siaga, bahkan terkesan tergagap. Koordinasi di antara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah kabupatan dan kota di Aceh, seperti tidak jalan. Kekuatan yang dimiliki TNI dan Polri sampai ke kecamatan, tidak dioptimalkan.
Padahal, kekuatan TNI dan Polri sangat memadai untuk menanggulangi bencana, seperti yang terlihat dalam gempa dan tsunami pada 2004 silam.
Harusnya, jauh sebelum ada peringatan bencana seperti diprakirakan BMKG, pemerintah kabupaten/kota di Aceh bisa menyiapkan diri. Namun, itu tidak terjadi sehingga semuanya terlihat gagap ketika banjir datang.
Pembicaraan beberapa tokoh dari kalangan aktivis dan akademisi, semuanya menyayangkan tidak sigapnya pemerintah kabupaten dan kota dalam melakukan mitigasi bencana. Selain koordinasi sesama pemangku kepentingan lemah, pemerintah juga terlihat bingung melakukan apa.
Sampai Jumat, 28 November 2025, korban banjir belum tertangani maksimal di beberapa tempat, di tengah banyak infrastruktur yang rusak. Pemerintah melalui instansi terkait harusnya sudah memiliki data dan titik pengungsi, serta menyalurkan bantuan tanggap darurat.
Di posko pengungsian warga masih bertahan dengan fasilitas seadanya. Anak-anak tidur di tikar tipis, sebagian tanpa selimut. Lansia dan ibu hamil belum seluruhnya mendapat layanan kesehatan memadai.
Sementara itu, akses jalan menuju desa terdampak masih terputus karena genangan air belum surut. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penanganan darurat masih jauh dari ideal—pelan, tidak terkoordinasi, dan kurang terencana.
Bantuan logistik pun tidak merata. Ada titik yang menerima tumpukan bantuan, sementara di titik lain warga harus menunggu berjam-jam hanya untuk mendapatkan mie instan dan air mineral. Ketimpangan distribusi ini menunjukkan lemahnya sistem data penerima bantuan, minimnya koordinasi lintas instansi, serta absennya skema pemetaan kebutuhan berdasarkan tingkat kedaruratan.
Di era digital, seharusnya pemerintah memiliki pusat data terpadu bencana untuk mempercepat keputusan, distribusi, dan komunikasi publik. Sistem pelaporan online yang melibatkan pemerintah, relawan, dan masyarakat dapat menjadi solusi untuk memperbaiki pola penanganan agar lebih cepat, akurat, dan terukur.
Peran TNI, Polri, dan relawan harus dioptimalkan bukan hanya pada evakuasi—tetapi juga pada pembukaan akses darurat, penyaluran logistik, dan pelayanan penyelamatan jiwa. Saat ini masih terlihat beberapa sektor bergerak sendiri-sendiri, bukan sebagai satu kesatuan komando penanganan bencana. Padahal dalam situasi kritis, kecepatan dan keseragaman langkah jauh lebih penting daripada formalitas prosedural.
Ke depan, Aceh harus belajar bahwa penanganan bencana tidak boleh dimulai ketika banjir telah merendam rumah dan jalan. Kesiapsiagaan harus menjadi budaya: latihan rutin, sistem evakuasi yang terencana, informasi yang presisi, dan kebijakan berbasis risiko.[]