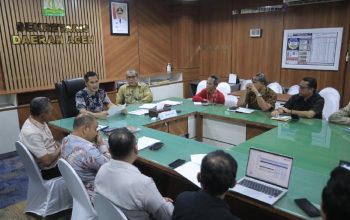Oleh: Akbar Rafsanjani*
Festival film sering kali dianggap sekadar pesta tontonan. Namun di Aceh, penyelenggaraan Aceh Film Festival (AFF) menyiratkan sesuatu yang lebih mendalam, ia adalah siasat kultural untuk bertahan di tengah keterbatasan infrastruktur, kebijakan, dan bahkan stigma terhadap seni itu sendiri. Tema tahun ini, “Stratagem”, menggarisbawahi hal tersebut.
Keterbatasan ruang ekspresi di Aceh bukan isu baru. Minimnya fasilitas menonton, absennya bioskop komersial, dan regulasi budaya yang sering lebih condong pada kontrol ketimbang perlindungan, membuat seniman harus mengandalkan strategi kreatif. Layar tancap di gampong, program komunitas, hingga kerja-kerja arsip dan dokumentasi menjadi bukti bahwa seni terus mencari jalannya sendiri. Dalam konteks itu, AFF bukan hanya festival, ia adalah bentuk perlawanan simbolik terhadap marginalisasi kebudayaan di Aceh.
Tulisan ini dibuat berdasarkan pada siaran langsung via Instagram @acehfilmfest yang dihadiri oleh Jamaluddin Phonna sebagai direktur festival dan Adli Dzil Ikram sebagai direktur program. Saya mencoba merangkum diskusi yang membahas secara detail program dan proses-proses di balik Aceh Film Festival 2025 yang akan dimulai pada tanggal 2 s.d. 6 September 2025 ini.
Secara programatik, AFF 2025 memperluas cakupan. Kompetisi Film Pendek Internasional dengan 3.000 submisi dari 120 negara adalah capaian strategis, menempatkan Aceh dalam orbit pertukaran global. Program Aflamu, yang menyorot film dari Timur Tengah, juga memperlihatkan kesadaran geopolitik. Aceh dan Timur Tengah berbagi persinggungan sejarah, budaya Islam, serta pengalaman kekerasan dan konflik. AFF seakan berkata bahwa film dapat menjadi medium lintas batas, menghubungkan pengalaman lokal dengan resonansi global.
Pilihan memutar No Other Land (dokumenter tentang perlawanan warga Palestina yang memenangkan Oscar) bukan sekadar program sinema, melainkan pernyataan politik. Ia menandai AFF sebagai ruang solidaritas transnasional, memperlihatkan bahwa festival di ujung barat Indonesia dapat berposisi dalam percakapan global tentang kolonialisme, pendudukan, dan kemanusiaan.
Namun di balik visi global itu, AFF juga mengingatkan kita pada ironi domestik. Di Aceh, ruang menonton yang representatif hampir tidak ada. Direktur AFF, Jamaluddin Phonna, menegaskan kebutuhan mendesak akan sebuah “gedung film”, ruang terpadu untuk produksi, pendidikan, hingga distribusi film. Selama kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, kerja-kerja komunitas dan festival akan selalu berada dalam posisi rentan, bergantung pada energi kolektif, dana hibah, atau jejaring solidaritas.
Di sini kita melihat AFF bukan sekadar acara seni, melainkan laboratorium sosial. Melalui program Forum Komunitas, festival ini mempertemukan berbagai kelompok untuk mendiskusikan ekosistem perfilman lokal. Upaya ini penting karena ia menggeser festival dari sekadar ajang selebrasi menuju arena deliberasi, tempat di mana masyarakat dapat merumuskan strategi bersama untuk membangun infrastruktur budaya.
AFF juga menunjukkan kesadaran estetika yang meluas. Kolaborasi dengan perupa Aceh untuk merancang artwork festival membuktikan bahwa ia bukan ruang eksklusif bagi film, melainkan titik temu seni lintas medium. Praktik ini memperkuat gagasan bahwa kebudayaan harus dipahami sebagai ekosistem, bukan sekadar sektor.
Pada akhirnya, Aceh Film Festival memperlihatkan bagaimana komunitas seni di Aceh menggunakan siasat (Stratagem) untuk bertahan dan berkembang. Ia adalah contoh konkret bahwa di tengah keterbatasan (baik politik maupun material) masyarakat tetap mampu menciptakan ruang alternatif bagi ekspresi, refleksi, dan perlawanan.
Karena itu, kehadiran publik bukan sekadar partisipasi pasif, melainkan bentuk dukungan langsung pada ekosistem budaya yang sedang dibangun. Aceh Film Festival akan berlangsung pada 2–6 September 2025, dengan venue utama di Theater Library dan Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Informasi selengkapnya dapat diikuti melalui Instagram @acehfilmfest.
Menonton di AFF adalah ikut serta dalam sebuah strategi kultural, memastikan bahwa seni tetap menjadi bagian vital dari kehidupan Aceh hari ini dan esok.[]
Editor: Ihan Nurdin

*Akbar Rafsanjani adalah kurator film, sekarang bermukim di Wisconsin, Amerika Serikat. Baca tulisan film lainnya di akun Letterboxd pribadinya: https://letterboxd.com/akbarrafs/films/reviews/