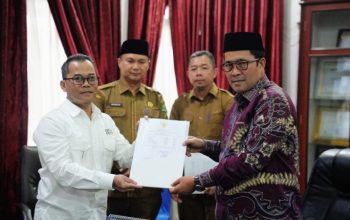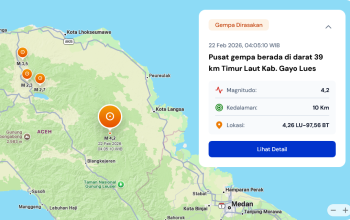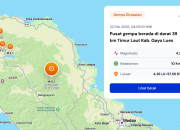Oleh dr. Suzanna Octiva, Sp.K.J.*
Di balik tawa dan canda di halaman sekolah, kaki-kaki kecil yang berlarian, seragam sekolah dan suara bel yang riuh, ada sesuatu yang tersembunyi kisah-kisah yang tak terdengar. Kisah anak-anak yang tampak baik-baik saja, tetapi membawa beban yang tak terlihat: ejekan, ancaman, pengucilan, atau perlakuan yang membuat mereka perlahan kehilangan kepercayaan diri. Ini sesungguhnya menggambarkan krisis yang tak kasat mata. Apakah ini adalah wajah lain dari dunia pendidikan kita—ketika bullying menjadi luka senyap yang menggerogoti masa depan mental anak-anak bangsa. Sebenarnya kita berada dalam suatu dilema antara harapan dan kenyataan. Harusnya sekolah merupakan tempat anak bangsa tumbuh dan belajar untuk menghadapi dunia. Namun, apakah sekolah benar-benar menyediakan ruang yang aman bagi mereka atau sekolah malah membuat luka sosial yang membayangi masa depan kesehatan mental mereka ?
Bullying, Luka yang Tidak Selalu Terlihat
Bullying atau perundungan bukanlah sekadar dinamika keseharian di sekolah, kasus biasa yang hilang dengan sendirinya. Setiap ejekan, hinaan, atau pengucilan meninggalkan jejak tak kasat mata di hati anak. Luka itu mungkin tak terlihat, tapi perlahan menorehkan keraguan, ketakutan, dan rasa tak berharga yang bisa membayangi mereka hingga dewasa. Menganggapnya sepele ibarat menutup mata pada badai yang mengamuk di dalam diri anak. Badai yang bila tidak ditangani, akan membentuk cara mereka melihat dunia dan diri mereka sendiri.
Bullying meninggalkan luka yang nyata di dalam otak. Saat seseorang terus-menerus di-bully, tubuhnya merasa terancam dan mengeluarkan hormon stres kortisol. Jika hal ini terjadi terus-menerus maka dapat menimbulkan kelelahan pada otak sehingga memengaruhi kerja otak.
Bagian otak yang mengatur emosi dan perasaan, seperti amigdala, menjadi lebih sensitif. Akibatnya, korban bullying jadi mudah cemas dan takut. Lalu, bagian otak yang membantu kita berpikir jernih dan mengendalikan diri, yaitu korteks prefrontal fungsinya akan bisa melemah. Hal ini membuat seseorang lebih sulit mengatur emosi dan mengambil keputusan dengan tenang.
Selain itu, hipokampus, bagian otak yang berperan dalam mengingat hal-hal penting, juga berpengaruh akibat stres yang berkepanjangan. Korban menjadi sulit fokus, cepat lupa, dan kehilangan semangat belajar.
Perubahan-perubahan di otak tersebut membuat korban bullying mengalami gangguan mental seperti depresi, kecemasan, atau merasa tidak berharga. Luka ini tidak terlihat dari luar, tapi sangat nyata dan bisa bertahan lama.
Seorang psikolog dan psikoanalisis asal Jerman Erik Erikson yang mengemukakan teori perkembangan psikososial (psychosocial development theory) menjelaskan bahwa masa kanak-kanak dan remaja adalah periode penting dalam pembentukan identitas diri. Dalam tahap industry versus inferiority, anak usia sekolah mulai menilai dirinya berdasarkan kemampuan dan pengakuan dari lingkungan. Sementara di tahap identity versus role confusion, anak berjuang menemukan siapa dirinya dan apa perannya di dunia. Di kedua tahap ini, rasa diterima dan rasa aman menjadi kebutuhan dasar. Ketika anak diterima, ia tumbuh percaya diri dan berani mencoba hal baru. Tapi ketika yang diterima justru ejekan dan penolakan, ia mulai meragukan dirinya. Bullying, dalam konteks ini, bukan hanya masalah sosial, tetapi juga ancaman terhadap perkembangan psikologis anak karena bullying menggagalkan proses penting: pembentukan identitas yang sehat.
Attachment: Kelekatan yang Menumbuhkan Kekuatan
Kelekatan atau attachment adalah benang halus yang menenun rasa aman seorang anak sejak dini. Peran orang tua sangatlah penting. Saat anak merasa diperhatikan, didengar, dan dicintai oleh orang tua benang itu menjadi fondasi yang menumbuhkan keberanian, rasa percaya diri, dan kemampuan menghadapi tantangan hidup.
Attachment yang sehat juga mengajarkan anak tentang empati. Anak yang merasakan cinta tanpa syarat belajar menghargai perasaan orang lain, sehingga kemungkinan mereka menjadi pelaku bullying pun berkurang. Dengan kata lain, orang tua tidak hanya melindungi anak dari menjadi korban, tetapi juga membentuk mereka menjadi individu yang peduli dan beradab.
Attachment juga harus dibangun di sekolah. Guru bukan hanya pengajar. Mereka adalah figur pengasuh kedua, penopang emosional ketika anak menghadapi kegagalan atau ejekan teman sebaya. Seorang guru yang memperlihatkan perhatian tulus — menanyakan kabar anak, mengamati perubahan perilaku, atau sekadar memberi pujian atas usaha kecil — secara diam-diam menanamkan rasa aman yang akan bertahan lama.
Tak kalah penting, teman sebaya juga berperan sebagai penyangga sosial. Dukungan teman yang memahami dan menerima anak tanpa syarat memperkuat rasa aman yang telah ditanam oleh orang tua dan guru. Bersama-sama, guru, orang tua, dan teman sebaya membentuk ekosistem emosional yang sehat—sekolah menjadi ruang di mana anak merasa dilindungi, didukung, dan berani tumbuh.
Sekolah Peduli Kesehatan Mental: Investasi untuk Masa Depan
Sekolah bukanlah hanya tempat mengenal angka, huruf dan sains. Lebih dari itu, sekolah adalah laboratorium pertama di mana anak-anak belajar memahami diri sendiri, membangun hubungan, dan menghadapi tekanan sosial. Sekolah yang peduli pada kesehatan mental bukanlah kemewahan, tetapi investasi nyata bagi masa depan anak-anak. Sekolah yang peduli pada kesehatan mental berarti menciptakan ruang aman, di mana anak merasa dihargai, didengar, dan terlindungi.
Dalam prakteknya sekolah peduli kesehatan mental dapat diwujudkan dalam beberapa kegiatan antara lain asesmen deteksi dini gangguan mental emosional secara berkala, layanan konseling yang mudah diakses (pojok curhat), pelatihan guru untuk mendeteksi tanda stres dan bullying, program edukasi emosional dan sosial (life skill), keterlibatan orang tua dan komunitas, kebijakan anti-bullying yang tegas dan jelas, kegiatan sosial berbasis nilai kemanusiaan dimana anak belajar berempati, kepedulian, dan tanggung jawab moral yang berakar pada nilai spiritual.
Menata Ulang Paradigma Pendidikan
Selama ini, pendidikan sering diukur dari kemampuan akademik, nilai ujian, dan prestasi yang terlihat di atas kertas. Padahal, anak-anak bukan hanya angka dan skor; mereka adalah manusia utuh dengan pikiran, emosi, dan kebutuhan psikologis yang harus diperhatikan. Sudah saatnya paradigma pendidikan ditata ulang: sekolah bukan hanya tempat belajar kognitif, tetapi juga laboratorium untuk menumbuhkan ketahanan mental, empati, dan rasa aman.
Sekolah peduli kesehatan mental memandang anak secara holistik, di mana prestasi belajar seiring dengan kesejahteraan emosional, sosial, dan spiritual. Di sini anak-anak belajar bahwa perasaan mereka valid, bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar, dan bahwa setiap individu berhak dihormati. Hal ini berarti kesehatan mental menjadi prioritas. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan aman, hangat, dan mendukung tidak hanya siap menghadapi tantangan akademik, tetapi juga membangun karakter yang kuat, mampu menjaga hubungan, dan menghadapi tekanan hidup tanpa takut. Paradigma baru ini menjadikan pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi perjalanan membentuk manusia seutuhnya.[]
Penulis adalah dokter spesialis kedokteran jiwa di Rumah Sakit Jiwa Aceh
Editor: Ihan Nurdin